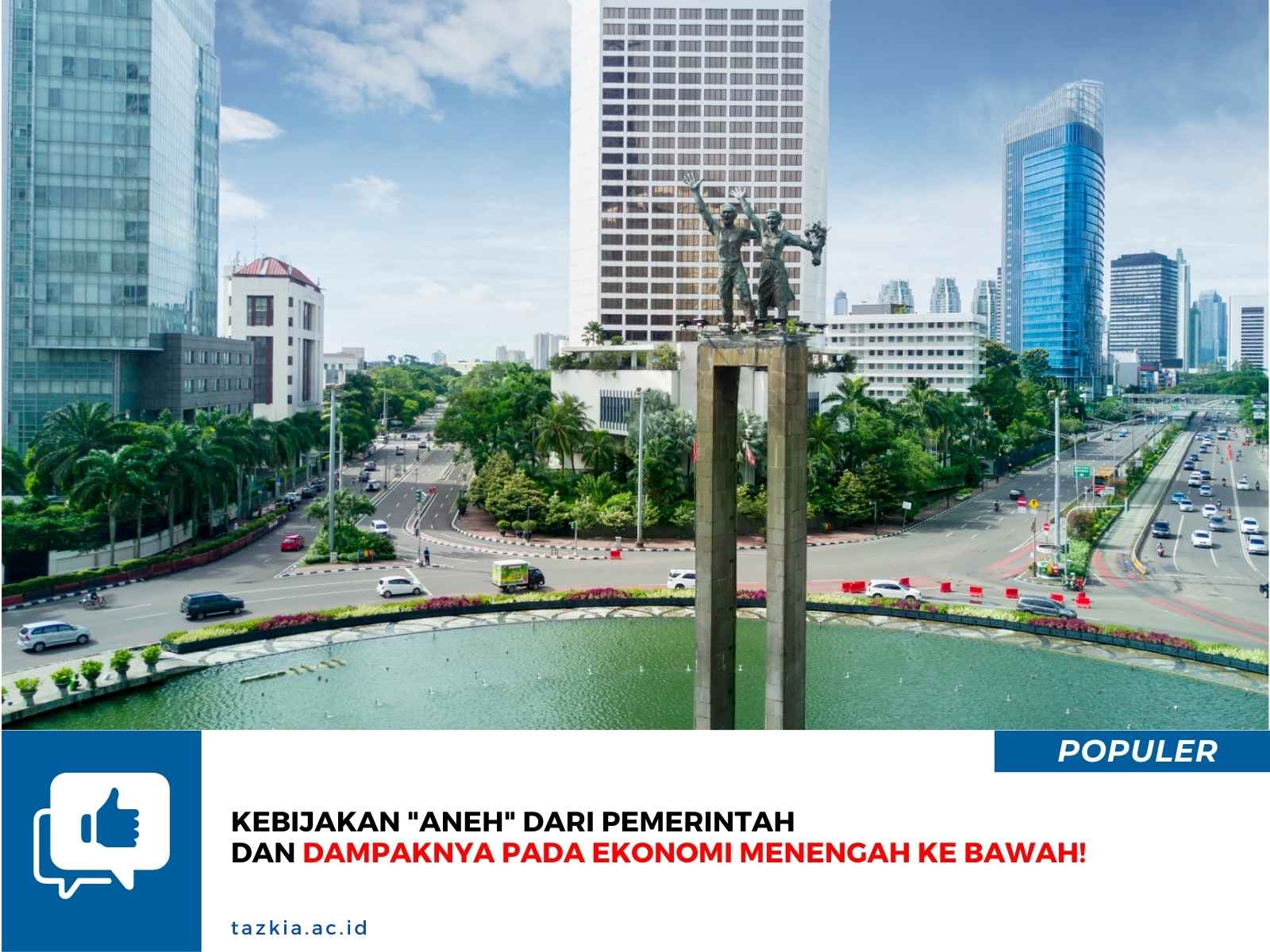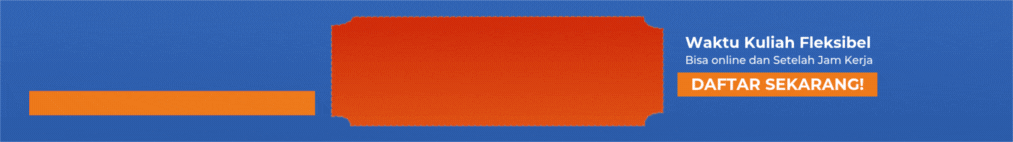Kelangkaan BBM dan PHK di SPBU Swasta
Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan curahan hati para pekerja SPBU swasta, seperti Shell, yang terkena PHK. Usut punya usut, PHK ini merupakan imbas dari kekosongan stok BBM di tempat mereka bekerja. Kelangkaan ini terjadi menyusul adanya kebijakan baru terkait kuota impor BBM.
Di tengah kebingungan publik, Menteri Bahlil memberikan solusi yang cukup mengejutkan. Ia menyarankan agar SPBU swasta yang kekurangan stok untuk "berkolaborasi" atau membeli BBM dari PT Pertamina (Persero). Pernyataan ini sontak menuai kritik. Banyak yang menilai solusi tersebut tidak masuk akal dan terkesan menyederhanakan masalah.
Bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan, "kolaborasi" bukanlah jawaban. Kebijakan yang tidak terencana dengan matang ini telah secara langsung mematikan sumber pendapatan mereka dan keluarga. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah regulasi dapat memutus rantai ekonomi yang selama ini sudah berjalan. Para pekerja SPBU, yang mayoritas adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, menjadi korban pertama dari kebijakan yang dianggap kurang bijaksana ini.
Rentetan Kebijakan Kontroversial Lainnya
Jika ditelusuri lebih jauh, kebijakan terkait SPBU swasta ini bukanlah satu-satunya yang menuai kritik. Sebelumnya, publik juga dibuat heboh dengan beberapa kebijakan dan pernyataan Bahlil lainnya yang dianggap "aneh" dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
Salah satunya adalah kebijakan penghapusan pengecer gas elpiji 3 kg. Dengan dalih untuk mengontrol harga dan distribusi agar tepat sasaran, kebijakan ini justru mematikan usaha para pedagang kecil di warung-warung. Masyarakat yang terbiasa membeli gas di dekat rumah kini harus mengantre panjang di pangkalan resmi. Lagi-lagi, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya.
Selain itu, Bahlil juga pernah menjadi sorotan karena kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai daerah yang membuat warga marah dan resah. Namanya bahkan sempat menjadi trending topic di media sosial sebagai bentuk protes publik atas kesulitan yang mereka hadapi.
Kritik Bukan Tanpa Dasar: Memutus Rantai Ekonomi
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan sebuah pola yang mengkhawatirkan. Alih-alih menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melindungi semua lapisan masyarakat, kebijakan yang dikeluarkan justru berpotensi mematikan usaha kecil dan menengah.
PHK massal di SPBU swasta dan hilangnya mata pencaharian pengecer gas adalah bukti nyata terputusnya rantai ekonomi. Para pekerja ini bukan sekadar angka statistik, mereka adalah tulang punggung keluarga yang kini harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup. Ketika satu sumber pendapatan hilang, dampaknya akan merembet ke sektor lain, mulai dari daya beli yang menurun hingga potensi peningkatan angka kemiskinan.
Kritik Konstruktif dan Perlunya Kajian Dampak Regulasi
Melihat pola kebijakan yang ada, kritik yang muncul bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah dorongan agar pemerintah menerapkan tata kelola yang lebih baik. Salah satu solusi fundamental adalah mewajibkan adanya Kajian Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment) yang transparan sebelum sebuah kebijakan diputuskan. Kajian ini harus secara komprehensif memetakan potensi dampak ekonomi dan sosial, terutama terhadap penyerapan tenaga kerja dan kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi negatif dan menyiapkan langkah mitigasi sejak awal, bukan bereaksi setelah masalah terjadi dan menimbulkan korban.
Solusi Konkret: Kebijakan Transisi dan Jaring Pengaman
Selain kajian pra-kebijakan, pemerintah perlu merancang mekanisme transisi yang jelas setiap kali akan menerapkan regulasi baru yang berisiko besar. Misalnya, dalam kasus kuota BBM, kebijakan dapat diterapkan secara bertahap untuk memberi waktu bagi pelaku usaha menyesuaikan diri. Jika perubahan tak terhindarkan, maka langkah berikutnya adalah membangun jaring pengaman sosial yang proaktif. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas terkait, seharusnya tidak menunggu viral. Sebaliknya, harus ada skema yang siap diaktifkan, seperti program reskilling (alih keahlian) bagi pekerja terdampak, fasilitasi akses modal usaha seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan program padat karya sementara. Pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif dengan asosiasi usaha serta serikat pekerja akan menciptakan iklim kebijakan yang lebih stabil dan adil bagi semua pihak.
Referensi:
-
Suara.com: BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Kompas.com: Viral PHK Karyawan SPBU Swasta Akibat Stok BBM Kosong, Kemenaker Beri Tanggapan
-
Detik.com: Kata Bahlil Soal Kabar Shell PHK Pekerja Imbas BBM Langka
-
Tempo.co: Bahlil Minta Pengelola SPBU Swasta Kerja Sama dengan Pertamina Ihwal Kekurangan Stok
-
Sindonews.com: 6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat